Oleh: Senopati Ananta Jayanegara
- Awal Kehidupan dan Pendidikan
1909 – Sutan Sjahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatra Barat. Ia tumbuh dari keluarga Minangkabau yang cukup berada; ayahnya seorang jaksa yang dikenal disiplin. Dari kecil, Sjahrir sudah dibiasakan pada nilai keteraturan, keterbukaan pada dunia modern, dan semangat belajar.
1917–1926 – Pendidikan formalnya dimulai di HIS Medan, kemudian melanjutkan ke MULO Medan, hingga ke AMS Bandung. Di AMS inilah kecerdasannya menonjol. Sjahrir bukan hanya gemar membaca, tetapi juga mengasah diri dalam musik, sastra, dan filsafat. Kecintaannya pada kebebasan berpikir tumbuh sejak remaja, menjadikannya berbeda dengan banyak pemuda sezamannya yang lebih memilih jalur praktis.
- Masa Mahasiswa di Belanda
1929 – Sjahrir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan hukum di Universiteit van Amsterdam. Di sana ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI), organisasi mahasiswa Indonesia yang berhaluan radikal anti-kolonial.
1930–1931 – Di Eropa, Sjahrir bergaul dengan mahasiswa internasional, membaca karya Marx, Kant, hingga tokoh-tokoh sosial-demokrasi Jerman. Ia kemudian menemukan jalan tengah: sosialisme demokratis. Berbeda dengan banyak kawan seperjuangannya yang tertarik pada komunisme, Sjahrir menolak totalitarianisme. Baginya, kemerdekaan harus seiring dengan kebebasan berpikir dan penghormatan terhadap hak-hak individu.
- Kembali ke Indonesia dan Politik Perlawanan
1931 – Sjahrir pulang ke tanah air, meski belum menuntaskan studinya. Ia merasa bangsa membutuhkan tenaga dan pikirannya lebih daripada gelar akademik. Bersama Mohammad Hatta, ia mendirikan Partai Indonesia Baru (PNI Baru). PNI Baru menekankan pendidikan politik bagi rakyat, bukan agitasi kosong.
1934 – Pemerintah kolonial Belanda menangkapi para pemimpin nasionalis nonkooperatif, termasuk Hatta dan Sjahrir. Mereka dibuang ke Boven Digoel, kemudian dipindahkan ke Banda Neira.
1935–1941 – Masa pengasingan ini justru menjadi “universitas kehidupan” bagi Sjahrir. Ia membaca karya-karya filsafat, berdiskusi dengan Hatta, sekaligus mengajar penduduk setempat. Dari sinilah terbentuk gaya kepemimpinannya: seorang intelektual yang memimpin dengan pikiran, bukan dengan pidato penuh slogan.
- Masa Pendudukan Jepang dan Gerakan Bawah Tanah
1942 – Jepang menduduki Indonesia dan membebaskan para tahanan politik. Namun, berbeda dengan sebagian nasionalis lain yang memilih kompromi, Sjahrir menolak bekerja sama dengan Jepang. Ia melihat Jepang sebagai kekuatan fasis yang sama berbahayanya dengan Belanda.
1943–1944 – Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-Jepang bersama para pemuda. Ia mengorganisir diskusi, menerbitkan selebaran gelap, dan menyiapkan generasi yang kelak mendorong proklamasi.
1945 – Setelah Jepang menyerah, Sjahrir menjadi tokoh penting yang mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan, tanpa menunggu restu Jepang. Baginya, revolusi sejati hanya lahir dari tekad rakyat, bukan hadiah penjajah.
- Perdana Menteri Republik Indonesia
14 November 1945 – Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Kabinetnya dikenal sebagai Kabinet Sjahrir I.
1946 – Ia memimpin perundingan dengan Belanda dalam Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947). Perjanjian ini membuat Belanda mengakui de facto kedaulatan RI di Jawa, Madura, dan Sumatera. Meski hasilnya dianggap terlalu kompromistis, langkah Sjahrir menyelamatkan republik muda dari isolasi diplomatik.
1947 – Tekanan politik dari oposisi semakin keras. Sjahrir dituduh terlalu “lembek” menghadapi Belanda. Pada 27 Juni 1947, ia mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Meski mundur, reputasinya sebagai negarawan berprinsip tetap melekat.
- Masa Partai Sosialis dan Kritik Demokrasi Terpimpin
1948–1950 – Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Melalui PSI, ia menegaskan jalan sosialisme demokratis: keadilan sosial tanpa mengorbankan kebebasan politik.
1955 – Dalam pemilu pertama, PSI hanya meraih suara kecil, kalah jauh dari PNI, Masyumi, dan NU. Namun Sjahrir tetap disegani sebagai intelektual dan guru politik.
1960 – Presiden Soekarno membubarkan PSI dengan alasan mengganggu stabilitas politik. Sejak saat itu, Sjahrir semakin tersisih dari arena politik resmi.
- Penangkapan, Pembuangan, dan Wafat
1962 – Sjahrir ditangkap dengan tuduhan subversif, tanpa pengadilan. Ia ditahan di Jakarta.
1965 – Kesehatannya merosot drastis di penjara. Setelah adanya tekanan internasional, ia diizinkan berobat ke luar negeri.
9 April 1966 – Sjahrir wafat di Zürich, Swiss, pada usia 57 tahun. Jenazahnya dibawa pulang dan dimakamkan di Jakarta dengan penghormatan kenegaraan.
- Warisan Pemikiran
Sjahrir adalah contoh pemimpin yang jarang: seorang intelektual murni yang masuk ke gelanggang politik, tanpa kehilangan prinsip. Ia menolak fasisme Jepang, menolak komunisme otoriter, dan juga menolak nasionalisme yang membabi buta. Bagi Sjahrir, revolusi adalah proses pembentukan manusia baru yang merdeka secara politik sekaligus bebas berpikir.
Karyanya “Perjuangan Kita” (1945) menjadi manifestonya: Indonesia merdeka tidak boleh jatuh ke dalam tirani, melainkan harus berakar pada demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan manusia.
Referensi
- Legge, J.D. Sutan Sjahrir: Democrat, Socialist, Indonesian Nationalist. Cornell University Press, 1977.
- Sjahrir, Sutan. Perjuangan Kita. 1945.
- Reid, Anthony. Indonesian National Revolution 1945–1950. Oxford University Press, 1974.
- Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press, 1952.
- Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia. Stanford University Press, 1981.
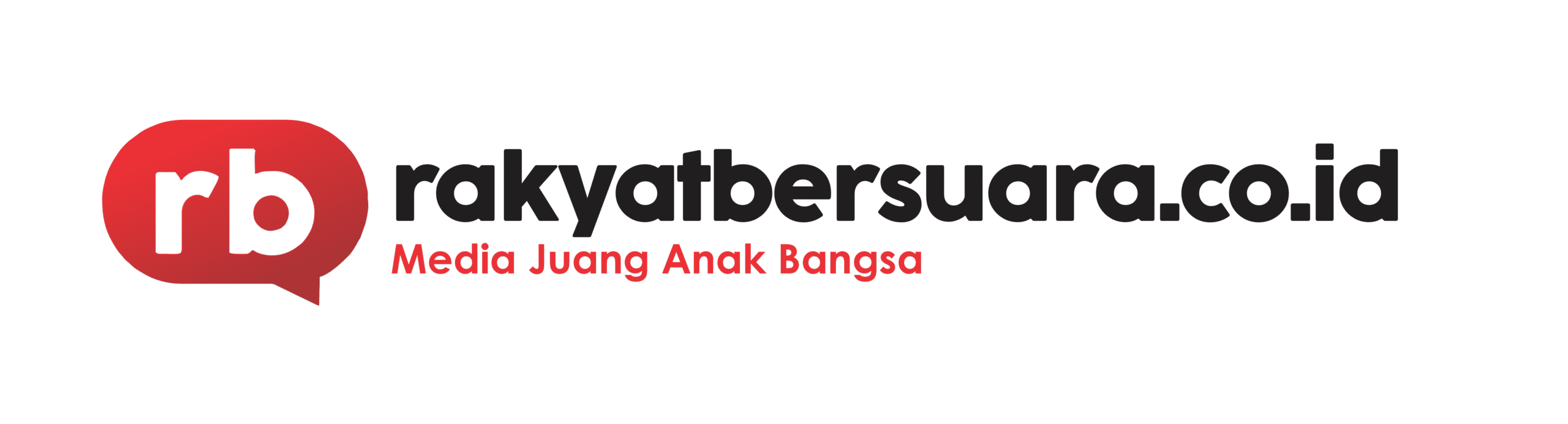










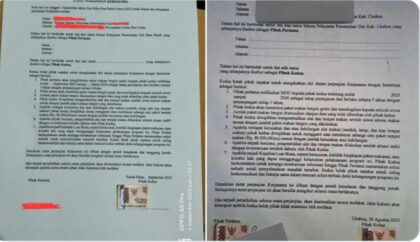

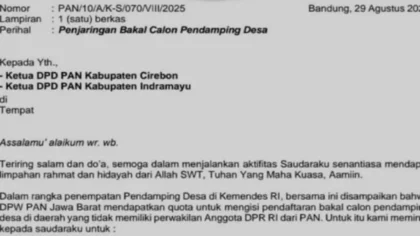
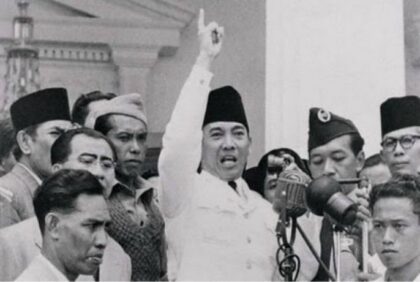




Komentar